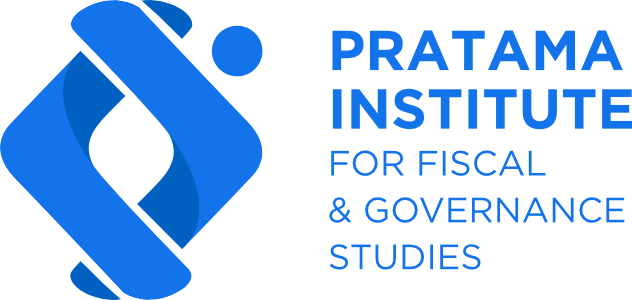Upah Minimum Provinis (UMP) 2024 resmi naik pada penghujung tahun ini. 35 Provinsi telah menyetorkan besaran angka UMP kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan kenaikan tertinggi tejadi di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp221.000.
Meskipun naik, namun kenaikannya masih menyisakan ragam persoalan. Pasca UMP 2024 diumumkan, gelombang protes diberbagai daerah belum mereda. Suara buruh bulat menuntut kenaikan UMP sebesar 15% dan menolak besaran UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerahnya masing-masing.
Selain itu, kebuntuan para policy maker dalam menentukan besaran UMP yang satu sisi harus meningkatkan kesejahteraan buruh namun di sisi lain wajib menjaga kelangsungan usaha, menjadi persoalan repetitif yang tidak jarang memantik gelombang demonstrasi dari para buruh.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2023 sebanyak 146,62 juta pekerja. Mirisnya 60,12% atau 83,34 juta diantaranya bekerja pada sektor informal dengan upah rata-rata di bawah standar.
BPS juga mencatat, rata-rata upah minimum buruh pada Februari 2023 hanya sebesar USD 189 atau Rp2,94 juta. GoodStatas mencatat upah ini terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan Malaysia (USD359) bahkan lebih rendah dari Kamboja (USD194).
Rendahnya upah buruh berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Saat pendapatan buruh terlalu timpang dengan inflasi, buruh pasti akan mengurangi konsumsinya dan daya beli akan menurun yang otomatis akan merugikan sektor konsumsi serta dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan memantik ketidakstabilan sosial yang secara simultan memperteruk iklim investasi. Imbas jangka panjangnya penerimaan negara semakin berkurang dari sisi pajak, bahkan PDB Indonesia bisa terdegradasi imbas menurunnya produktivitas buruh akibat upah minimum yang di bawah standar.
83,34 juta orang merasakan upah dibawah standar walaupun kontribusi mereka terhadap Pajak Domestik Bruto (PDB) tidak bisa dianggap sepele. BPS mencatat Indonesia memiliki PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) senilai Rp19.588,4 triliun pada 2022, dan 65,58% diantaranya disumbang oleh sektor industri yang ditopang oleh buruh.
Sayangnya kontribusi buruh yang sangat besar terhadap PDB tidak diimbangi dengan besaran upah aktual buruh, setidaknya untuk gaji pokok mereka. Idealnya upah aktual berkaitan dengan bonus kinerja, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan insentif penjualan. Tapi nyatanya fasilitas seperti ini masih dirasa terlalu mewah untuk buruh terutama para buruh di sektor informal.
Nasib buruh di sektor formal juga tidak jauh berbeda. Faktanya kebanyakan pengusaha juga menjadikan UMP sebagai upah maximum untuk para buruh tanpa adanya kenaikan upah secara berkala. Mulanya UMP dimaksudkan sebagai jaring pengaman bagi buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun, namun faktanya banyak Perusahaan menggunakan UMP sebagai standar upah kepada buruh yang bekerja selama bertahun-tahun. Dalam hal negosiasi upah, buruh selalu dihadapkan pada situasi tawar menawar yang lebih rendah ketimbang pengusaha, mengapa? Mayoritas buruh sangatlah bergantung pada pekerjaan mereka untuk memenuhi segala kebutuhan dasar yang acapkali menyeret buruh pada sikap pasrah menerima upah yang telah ditetapkan.
Kenaikan UMP yang terlalu tinggi akan berdampak pada kenaikan biaya tenaga kerja. Biaya produksi turut naik imbas dari kenaikan biaya tenaga kerja terutama di sektor-sektor industri yang tenaga kerjanya merupakan komponen biaya yang siginifikan seperti sektor jasa dan industri manufaktur yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
Jika buruh selalu terseret dalam posisi tawar menawar yang lemah ketika adanya negosiasi kenaikan gaji, hal demikian nyaris tidak berlaku untuk pengusaha. Sebagai pemilik modal, mereka memiliki jalan keluar yang lebih beragam daripada buruh. Mereka bisa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, memindahkan pabrik atau bisnisnya ke negara dengan upah minimum yang lebih kecil, bahkan menghentikan investasi bisnis mereka atau beralih pada otomatisasi yang notabene akan menurunkan keterserapan tenaga kerja.
Di tengah kebuntuan tersebut, pemerintah sebagai regulator dianggap memiliki keberpihakan terhadap pengusaha. Narasi formulasi kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan kelompok buruh sering menghiasi panggung demonstrasi. Namun apakah benar pemerintah tidak berpihak pada buruh?
Pemerintah bukan tanpa upaya agar buruh mempunyai kehidupan yang lebih sejahtera, dengan rutin berdialog secara tripatrit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah dengan harapan mencapai keputusan yang ideal terkait besaran UMP walau selalu berujung kebuntuan.
Salah satu alasan mengapa kenaikan UMP cenderung tidak signifikan setiap tahun ialah akibat kualifikasi pendidikan buruh yang masih tergolong rendah. BPS mencatat Tenaga Kerja Indonesia didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) kebawah yakni sebanyak 39,76%. Angka tersebut berbanding terbalik dengan Tenaga Kerja lulusan S1 yang hanya sebesar 9,31%. Akibatnya hal tersebut berpengaruh pada Tingkat produktivitas buruh karena minimnya tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi industri.
Selain Pendidikan, nilai output para buruh yang cenderung rendah juga menjadi pertimbangan. Mayoritas pengusaha hanya akan membayar pekerja sesuai nilai output yang mereka hasilkan. Data dari International Labour Organization (ILO) mencatat setiap satu jam kerja, satu pekerja Indonesia menghasilkan USD12,96 terhadap PDB. Produktivitas ini berada di bawah negara ASEAN lainnya seperti Malaysia (USD25,59) dan Thailland (USD15,06), akibatnya rasio ekspor Indonesia terhadap PDB cenderung jadi yang terendah se ASEAN. Hal yang sama juga berlaku pada rasio perdagangan, World Bank mencatat rasio perdagangan Indonesia jadi yang terendah di ASEAN (43,02%) dari PDB, angka tersebut jauh lebih rendah bahkan dari Laos (75,83%).
Solusi Kolaboratif
Dalam menghadapi tajamnya dilema UMP, menjadi jelas bahwa perdebatan antara kebutuhan buruh dan keberlanjutan usaha membutuhkan solusi yang bijaksana dan seimbang dari semua pihak.
Pemerintah sebagai regulator dapat menerapkan kebijakan UMP dengan mempertimbangkan pendekatan diferensiasi. Misalnya, sektor industri yang memiliki biaya hidup lebih tinggi atau berada di wilayah dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi dapat diberi kenaikan upah yang lebih besar daripada sektor atau wilayah lain yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Selain itu Implementasi kenaikan UMP harus dilakukan secara bertahap untuk memberikan waktu bagi pengusaha dalam menyesuaikan diri dengan biaya tambahan. Pendekatan ini dapat membantu mencegah tekanan yang berlebihan pada perusahaan.
Selain itu kebijakan fiskal yang bijaksana juga menjadi faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Pemerintah harus rutin menyediakan insentif bisnis untuk perusahaan yang rutin berinvestasi dalam hal mengedukasi atau memberikan pelatihan pada karyawannya.
Pada akhirnya rendahnya UMP hanya akan menyisakan jejak kemiskinan yang sulit dihapuskan. Buruh dengan upah minim acapkali terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Jangankan menabung, apalagi menlanjutkan pendidikan, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja acapkali kesulitan. Rendahnya UMP menjadi hambatan utama bagi buruh untuk melakukan mobilitas sosial. Hal tersebut membuat buruh semakin terpinggirkan dari standar kehidupan yang layak.
Maka dibutuhkan kolaborasi yang aktif dari pemerintah, pengusaha tak terkecuali buruh agar persoalan UMP tidak meninggalkan persoalan yang berkepanjangan. Dengan demikian, kesejahteraan buruh dapat beriringan dengan kepentingan pengusaha dan tak lagi menjadi dilemma yang berlarut-larut bagi pemerintah.
Artikel ini telah tayang di Harian Bisnis Indonesia dengan judul “Tajamnya Dilema UMP”, pada 23 Desember 2023 dengan tautan https://koran.bisnis.com/read/20231223/251/1726607/opini-tajamnya-dilema-ump